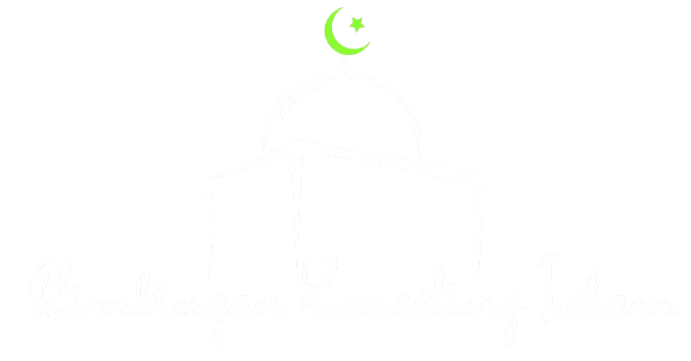5 Tahun lalu Pandemi Covid-19 bukan sekadar bencana medis. Ia juga adalah badai emosional yang menyapu ruang-ruang kesadaran manusia, terutama bagi mahasiswa yang tiba-tiba harus belajar dari rumah, berjauhan dari teman, dosen, dan ritme akademik yang sebelumnya terasa normal. Dalam keterpaksaan itu, mereka dituntut tetap tangguh—tapi bagaimana kita tahu seperti apa emosi yang mereka rasakan?
Sebuah studi yang dilakukan oleh Budi Sarasati dan Okta Nurvia dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mencoba menjawab pertanyaan itu melalui cara yang unik: menelusuri emosi mahasiswa melalui tulisan. Dengan pendekatan psikolinguistik dan metode campuran, mereka mengumpulkan narasi personal dari 43 mahasiswa yang menuliskan perasaan mereka selama mengikuti kuliah daring.
Kata yang Menggambarkan Diri
Pertanyaan pertama dalam studi ini sederhana namun reflektif: Apa padanan kata dari ‘tangguh’ menurutmu? Mayoritas menjawab dengan kata “kuat”, disusul “perkasa” dan “tegar”. Ternyata, di balik kalimat-kalimat digital yang mereka kirimkan, ada usaha untuk tetap berdiri tegak, meski dunia di luar sedang goyah.
Namun yang menarik, definisi ‘tangguh’ tidak berhenti pada kekuatan fisik. Banyak dari mereka yang mengaitkan tangguh dengan ketahanan batin: bisa bangkit saat jatuh, tetap optimis meski gelombang tugas datang bertubi-tubi, serta kemampuan untuk mengontrol diri di tengah ketidakpastian.
Menyuarakan Emosi Lewat Tulisan
Apa yang terjadi ketika emosi tak bisa disalurkan lewat tatap muka? Tulisan menjadi jembatannya. Dari lembar kerja yang dikumpulkan, muncul berbagai ekspresi: takut, bingung, sedih, kesal, jenuh, bahkan muak. Beberapa mengaku takut akan masa depan, takut nilai menurun, atau takut tak bisa membantu keluarga yang terdampak.
Ada juga yang merasa jenuh luar biasa karena tak bisa keluar rumah atau bertemu teman. “Saya merasa terkurung dalam rutinitas yang tak memberi ruang untuk bernafas,” tulis seorang mahasiswa. Tapi tak semua kelabu—di antara keluhan, muncul juga rasa syukur karena lebih sering berkumpul dengan keluarga.
Emosi Itu Nyata dan Tak Boleh Diabaikan
Sebanyak 93% mahasiswa mengatakan bahwa tulisan mereka benar-benar mencerminkan apa yang mereka rasakan. Ini menjadi sinyal penting bahwa ekspresi tertulis bukan sekadar tugas formal. Ia adalah luapan emosi yang jujur, spontan, dan menyimpan energi psikologis yang bisa meledak jika tak mendapat ruang.
Tulisan, dalam konteks ini, menjadi semacam terapi. Bahasa menjadi alat untuk membebaskan emosi yang tertahan. Seperti yang dikatakan Goleman (2002), emosi bukan hanya soal perasaan, tapi juga proses kognitif yang melibatkan penilaian, persepsi, bahkan dorongan untuk bertindak.
Tangguh, Tapi Tak Selamanya Kuat
Menariknya, meski mayoritas merasa tangguh, hanya sedikit yang menilai dirinya berada di tingkat sangat tangguh. Banyak yang mengaku berada di zona sedang atau bahkan rendah. Mereka merasa mudah panik, takut berbuat salah, atau merasa tidak nyaman berada dalam sistem belajar daring yang membingungkan dan tidak manusiawi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ketangguhan bukanlah sesuatu yang absolut. Ia dinamis, dipengaruhi oleh lingkungan, pola interaksi, dan cara seseorang memaknai situasi. Maka, penting bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk tidak sekadar menilai hasil belajar, tapi juga menyelami dunia emosional mahasiswa.
Menulis: Media Relaksasi dan Kesehatan Mental
Tulisan tak hanya menjadi alat komunikasi. Ia bisa menjadi media coping, tempat menuang luka secara sehat. Dalam dunia pendidikan, menulis bisa dijadikan bagian dari terapi psikologis ringan—cara yang murah namun berdampak untuk membantu mahasiswa memahami dan menerima dirinya sendiri.
Hal ini sejalan dengan gagasan self-regulated learning (Zimmerman & Schunk, 2011), yang menekankan pentingnya kesadaran diri, motivasi, dan perilaku yang dikelola secara mandiri dalam proses belajar. Jika emosi positif bisa ditumbuhkan, maka motivasi intrinsik pun akan lebih kuat.
Refleksi dan Harapan
Emosi adalah jendela jiwa. Melalui tulisan, kita bisa melihat apa yang tak terucap. Studi ini menunjukkan bahwa menulis bukan hanya tugas akademik, tapi juga bentuk kejujuran emosional. Dalam situasi seperti pandemi, kita butuh lebih banyak ruang-ruang ekspresi yang aman, sehat, dan membebaskan.
Esai ini bukan sekadar refleksi terhadap satu penelitian, tapi juga seruan: bahwa dalam setiap kalimat yang ditulis mahasiswa, ada cerita yang tak boleh diabaikan. Dan mungkin, yang dibutuhkan pendidikan hari ini bukan hanya modul daring yang efektif, tapi juga ruang empati—tempat mahasiswa bisa berkata, “Aku lelah, tapi aku ingin tetap belajar.” []